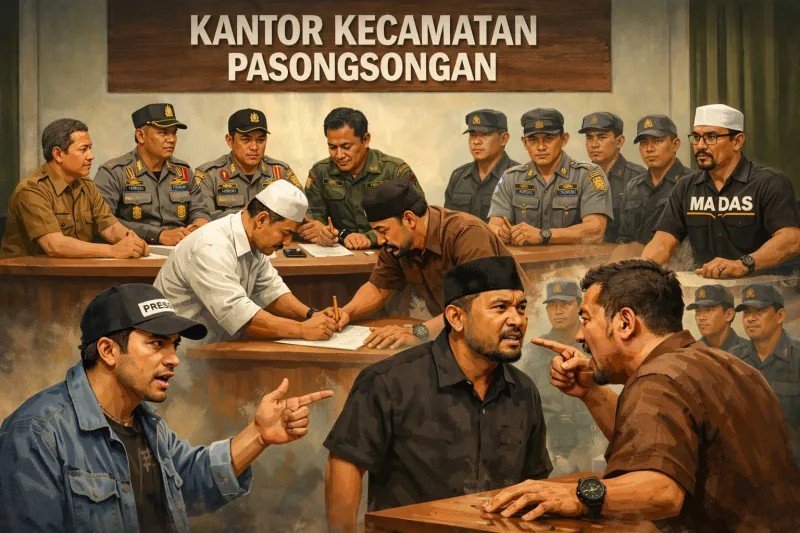Jakarta — Seputar Jagat News. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tengah memasuki fase krusial. Di tengah upaya mengejar penyelarasan dengan KUHP baru yang telah disahkan, muncul kritik tajam dari berbagai pihak terhadap sejumlah pasal yang dinilai melemahkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya pada mekanisme praperadilan dan upaya paksa.
Salah satu isu sentral yang memicu perdebatan adalah pengaturan praperadilan dalam draf RUU KUHAP terkini. Padahal, lembaga ini selama ini menjadi alat penting bagi warga negara untuk menguji legalitas tindakan aparat penegak hukum.
Mekanisme praperadilan selama ini dianggap belum ideal. Dalam kondisi saat ini, proses praperadilan hanya dapat dilakukan setelah terjadi pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan upaya paksa (post factum), hanya menyentuh aspek formil, dan dibatasi waktu pemeriksaan maksimal 7 hari—yang otomatis gugur jika perkara pokok telah disidangkan.
Namun, alih-alih memperkuat fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum, RUU KUHAP justru dinilai menyempitkan cakupan objek praperadilan. Hal ini terlihat dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a, yang menyatakan:
“Upaya paksa yang telah mendapatkan izin ketua pengadilan negeri tidak termasuk dalam objek praperadilan.”
Ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 (Putusan 21), yang telah menetapkan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan adalah bagian dari objek praperadilan. MK menilai, KUHAP tidak secara tegas mengatur jumlah minimal alat bukti yang diperlukan dalam penetapan tersangka—berbeda dengan UU No. 30/2002 yang menyebutkan minimal dua alat bukti.
Putusan MK bahkan menyebut bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang sah disertai pemeriksaan terhadap calon tersangka, kecuali untuk kasus in absentia.
Di tengah perdebatan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: Haruskah penetapan tersangka menjadi objek praperadilan?
Secara konseptual, tidak masuknya penetapan tersangka dalam ruang lingkup praperadilan memang tidak salah mutlak. Dalam sistem due process model yang dianut Indonesia, sejumlah negara telah menolak memasukkan penetapan tersangka ke dalam mekanisme judicial review.
Namun, MK dalam Putusan 21 menggarisbawahi bahwa tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka berpotensi menjadi bentuk perampasan HAM, sehingga perlu dibuka ruang kontrol melalui praperadilan.
Sebaliknya, Hakim Konstitusi Gede Palguna dalam pendapat berbeda menyatakan bahwa tidak dimasukkannya penetapan tersangka ke dalam praperadilan tidak melanggar hukum internasional dan tidak otomatis menimbulkan tanggung jawab negara.
Hakim Aswanto pun menilai, memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan bukan soal tafsir, melainkan membuat norma baru yang berada di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Selain praperadilan, standar pelaksanaan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan dalam RUU KUHAP juga menuai kritik.
Misalnya, dalam Pasal 89, disebutkan bahwa penangkapan tidak memerlukan izin pengadilan—kecuali tertangkap tangan. Bahkan, Pasal 90 ayat (2) membuka ruang penangkapan dalam waktu tidak terbatas jika tempat penangkapan jauh dari kantor penyidik.
Penjelasan pasal tersebut mencontohkan kondisi geografis sebagai justifikasi, namun tidak memberikan batasan yang ketat, sehingga berpotensi disalahgunakan. Bahkan, tidak ada kewajiban menghadapkan tersangka ke hakim dalam jangka waktu tertentu.
Padahal, menurut standar internasional (ICCPR), seseorang yang ditangkap harus dihadapkan secara fisik ke hakim dalam waktu 48 jam untuk menguji legalitas penangkapan.
Lebih lanjut, Pasal 90 ayat (3) memungkinkan penangkapan diperpanjang tanpa batas waktu, selama dihitung sebagai masa penahanan. Namun ini dinilai bermasalah, karena penahanan dan penangkapan adalah dua tindakan hukum berbeda, dengan syarat dan tujuan yang tidak sama.
RUU KUHAP juga memperluas alasan penahanan yang diatur dalam Pasal 93 ayat (5). Beberapa alasan dinilai terlalu elastis dan subyektif, seperti:
- Memberikan informasi yang tidak sesuai fakta saat pemeriksaan
- Tidak bekerja sama dalam pemeriksaan
- Menghambat proses pemeriksaan
Ketentuan ini dinilai bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana, karena memberikan informasi yang tidak sesuai merupakan hak ingkar yang dimiliki tersangka.
RUU ini juga tidak menjelaskan standar objektif untuk menilai alasan-alasan tersebut, membuka ruang penyalahgunaan dalam praktik.
Ketentuan mengenai penggeledahan dalam Pasal 105 huruf e dan Pasal 106 ayat (4) dinilai tidak konsisten, khususnya untuk informasi elektronik. RUU KUHAP tidak membedakan antara penggeledahan data dengan penggeledahan perangkat elektroniknya.
Frasa “keadaan mendesak” juga hanya dijelaskan dalam bagian Penjelasan, bukan dalam batang tubuh pasal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
Dalam Pasal 112 ayat (2), RUU KUHAP tidak mengatur batas waktu pemberitahuan kepada pengadilan pasca penyitaan mendesak. Tidak diaturnya mekanisme penolakan izin penyitaan juga berpotensi membuat barang sitaan tidak bisa dikembalikan secara adil.
Penyadapan merupakan bentuk pelanggaran privasi paling serius, namun RUU KUHAP tidak membatasi jenis tindak pidana yang dapat disadap. Idealnya, penyadapan hanya untuk tindak pidana berat dan kompleks seperti:
- Terorisme
- Pencucian uang
- Perdagangan orang
- Korupsi
- Kejahatan transnasional lainnya
Lebih lanjut, RUU ini juga belum mengatur mekanisme pemberitahuan penyadapan kepada individu yang disadap. Padahal, hal ini penting agar mereka bisa menggunakan hak-haknya, seperti mengajukan penghapusan data, memperoleh ganti rugi, atau bahkan mengajukan keberatan atas tindakan tersebut.
RUU KUHAP sejatinya hadir untuk memperkuat sistem hukum acara pidana Indonesia agar lebih berkeadilan dan menghormati HAM. Namun sejumlah ketentuan dalam draf terbaru justru menimbulkan kekhawatiran bahwa revisi ini bisa menggerus prinsip-prinsip perlindungan hukum, terutama terhadap warga negara yang berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Pengawasan yang lemah terhadap upaya paksa, penetapan tersangka, hingga penyadapan, berpotensi menjadikan RUU ini alat legitimasi kesewenang-wenangan.
Pemerintah dan DPR diminta berhati-hati dan terbuka terhadap masukan publik, agar revisi KUHAP tidak menjadi langkah mundur dalam penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. (MP)